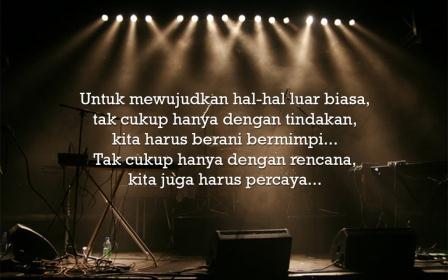Latar Belakang
Kitab suci Al-Qur’an mempunyai daya tarik yang tidak habis untuk dipahami, dikaji, dan diteliti secara akademis. Keberadaan dan keistimewaan Al-Qur’an secara historis-empiris telah melahirkan ribuan karya tafsir. Beragam tafsir itu muncul sejak kitab suci ini ada hingga masa kini, ribuan tahun kemudian. Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban, semakin banyak muncul karya-karya tafsir dengan berbagai macam varian.
Menguikuti perjalanan sejarah yang selalu berkembang, penafsiran terhadap Al-Qur’an tidak henti-henti dilakukan, berawal sejak diturunkannya Al-Qur’an hingga batas akhir yang tidak dapat ditentukan. Munculnya kitab tafsir yang sarat dengan berbagai macam metode maupun pendekatan merupakan bukti nyata bahwa upaya penafsiran Al-Qur’an tidak pernah berhenti.
Tafsir, pada masa ke masa senantiasa mengalami pertumbuhan. Bermula pada zaman Nabi, sahabat, tabi’in, atba’ut tabi’in, hingga pada masa modern-kontemporer. Adapun pada permulaannya tafsir tidaklah dibukukan, akan tetapi hanyalah diriwayatkan melalui mulut ke mulut (tradisi oral). Baru setelah masa tabi’in tafsir menglamai pembukuan dan hingga seterusnya mengalami pertumbuhan hingga pada saat sekarang ini.
Bukan hanya perubahan yang awalnya tidak tafsir tidak dibukukan menjadi dibukukan, akan tetapi dari masa ke masa tafsir juga mengalami perubahan genre.
A. Tafsir Al – Qur’an Pada Periode Pembukuan
Tafsir di era Nabi, sahabat, dan permulaan tabi’in sering dikategorikan sebagai tafsir periode pertama atau era Qabla al-Tadwin, yakni sebelum dikodifikasikannya kitab-kitab hadits dan tafsir secara mandiri. Tafsir-tafsir yang muncul di era formatif-klasik[1] ini masih sangat kental dengan nalar bayani dan bersifat deduktif, di mana teks al-Qur’an (nash) menjadi dasar penafsiran dan bahasa menjadi perangkat analisisnya. Oleh karena itu, sangat wajar jika Nasr Hamid sering menyebut peradaban Arab sebagai peradaban teks (hadlarah an-nash). Dengan kata lain, mereka lebih suka menggunakan “nalar langit” (deduktif) daripada “nalar bumi” (induktif).
Tradisi penafsiran era formatif cenderung menggunakan model nalar quasi-kritis. Ciri-ciri menonjol dari nalar ini adalah pengunaan metode periwayatan, symbol-simbol tokoh, menghindari Ra’yu (rasio), dan minimnya budaya kritisisme dalam menafsirkan Al-Qur’an serta penggunaan riwayat-riwayat israiliyat (yang tidak jelas kebenarannya), namun diterima sebagai kebenaran.[2] Akan tetapi penafsiran dengan penggunaan riwayat-riwayat israiliyyat baru marak terjadi pada masa tabi’in.
Sedangkan tafsir periode kedua bermula dari masa kodifikasi hadits secara resmi, yakni pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) di mana ketika itu tafsir masih digabung dengan hadits dan dihimpun dalam satu bab sperti bab-bab hadits. Sudah barang tentu kebanyakan tafsir yang ditulis adalah tafsir bil ma’tsur (ilmu-ilmu periwayatan) untuk membedakannya dari al-ulum al-‘aqliyah (ilmu-ilmu rasional), seperti filsafat dan matematika.[3] Periode kedua ini berlanjut hingga munculnya kodifikasi tafsir secara khusus dan terpisah dari hadits, yang oleh para ahli diduga oleh era Al-Farra’ dengan kitabnya Ma’ani al-Qur’an.[4]
Periode ketiga terjadi pada era pasca tabi’in atau lebih tepatnya pada generasi atba’ut tabi’in. para tokoh tafsir periode ini, antara lain: Yazid bin Harun (w. 117 H), Syu’bah bin Hajjaj (w. 160 H), Waki’ bin Jarah (w. 197 H), Sufyan bin Uyainah (w. 198 H), Abdur Rozaq (w. 211 H). Namun, sayangnya karya tafsir-tafsir mereka tidak sampai ke tangan kita, kecuali sekedar nukilan-nukilan. Barangkali hanya kitab Ma’ani Al-Qur’an karya Al-Farra’ yang sampai ke tangan kita.[5] Kemudian barulah setelah itu para ulama membuat tafsir yang lengkap mengenai al-Qur’an dan sesuai berdasarkan urutan ayat dari al-Qur’an. Ulama tersebut yang paling masyhur diakui sebagai peletak tafsir sesuai urutan ayat dalam al-Qur’an adalah Ibn Jarir Ath-Thabari (w. 310 H).[6] Pada masa inilah pembukuan tafsir dilakukan secara khusus, yang menurut para sejarawan dimulai pada akhir masa Dinasti Umayyah dan awal Dinasti Abbasiyyah.
Masa pembukuan dimulai pada akhir dinasti Bani Umayyah dan awal Dinasti Abbasiyyah. Dalam hal ini hadits mendapat prioritas utama dan pembukuannya meliputi berbagai bab, sedang tafsir hanya merupakan salah satu bab dari sekian banyak bab yang dicakupnya. Pada masa ini penulisan tafsir belum dipisahkan secara khusus yang hanya memuat tafsir Al-Qur’an, surah demi surah dan ayat demi ayat, dari awal al-Qur’an sampai akhir.[7]
Adapun penyebaran tafsir pertama kali adalah dinukil melalui mulut ke mulut, kemudian ditulis akan tetapi masuk dalam bab-bab hadits, barulah kemudian dibukukan secara tersendiri dan diikuti juga dengan tafsir bil-ma’tsur dan tafsir Bi al-Ra’yi.[8]
Secara garis besar tafsir Al Qur’an pada periode pertengahan ini diklasifikasikan menjadi lima periode, yaitu:[9]
(1) Periode I, pada zaman Bani Muawiyah dan permulaan zaman Abbasiyah yang masih memasukkan ke dalam sub bagian dari hadits yang telah dibukukan sebelumnya.
(2) Periode II, telah dilakukan pemisahan tafsir dari hadits dan dibukukan secara terpisah menjadi satu buku tersendiri. Dengan meletakkan setiap penafsiran ayat dibawah ayat tersebut. seperti yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At Thobary, Abu Bakar An Naisabury, Ibnu Abi Hatim, dengan mencantumkan sanad masing-masing penafsiran sampai ke Rasulullah, sahabat, dan tabi’in.
(3) Periode III, membukukan tafsir dengan meringkas sanadnya dan menukil pendapat para ulama tanpa menyebutkan orangnya. Hal ini menyulitkan dalam membedakan antara sanad yang shahih dan yang dhaif yang menyebabkan para mufassir berikutnya mengambil tafsir ini tanpa melihat kebenaran/ kesalahan dari tafsir tersebut.
(4) Periode IV, pembukuan tafsir banyak diwarnai dengan buku-buku terjemahan dari luar Islam. Sehingga pada periode ini juga terjadi spesialisasi tafsir menurut bidang keilmuan para mufassirnya.
(5) Periode V, tafsir maudhui yaitu tafsir dibukukan menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan. Seperti yang ditulis oleh Ibn Qoyyim dalam bukunya At Tibyan Fi Aqsamil Al Qur’an, Abu Ja’far An Nukhas dengan Nasih wal Mansukh, Al Wahidi dengan Asbabun Nuzul, dan Al Jassos dengan Ahkamul Qur’annya.
Periode pertengahan ini dimulai dengan munculnya produk penafsiran yang sistematis dan sampai ke tangan generasi sekarang dalam bentuk buku. Dalam peta sejarah pemikiran Islam, periode pertengahan dikenal sebagai zaman keemasan ilmu pengetahuan. Perhatian resmi dari pemerintahan dalam hal ini menjadi stimulus yang sangat signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan sendiri.
Setelah periode sahabat beserta tabiin, pergerakan dari pertumbuhan tafsir mengalami kemajuan seiring dengan dimulainya pembukuan terhadap hadits Nabi Saw. Gerakan pembukuan ini merupakan kebijakan dan jasa dari penguasa (khalifah) yang berkuasa pada saat itu (masa akhir dari Dinasti Umayyah dan awal Dinasti Abbasiyyah).
Pada akhir abad ke-3 H dan permulaan abad ke-4 H, geliat tafsir mengalami perubahan genre. Dari pembukuan yang masih menjadi satu dengan hadits-hadits selain tafsir, menuju pembukuan tersendiri yang hanya memuat riwayat-riwayat tafsir dan sesuai dengan urutan ayat-ayat Al Qur’an. Ibn Jarir al Thabari (w. 310 H) diakui sebagai orang pertama yang melakukan terobosan besar ini melalui karyanya Jami’ al Bayan fi Ta’wil Ay Al Qur’an.[10]
Tafsir pada generasi ini masih menggunakan metode riwayat (naql atau ma’tsur) dari hadits Nabi Saw, sahabat, maupun tabiin, dan ulama-ulama setelahnya (tabi’ al-tabi’in) lengkap dengan sanadnya. Tak terkecuali tafsir milik Al Thabari yang sering menyelipkan pendapat-pendapat ulama (baik dalam masalah gramatika Bahasa Arab, mazhab fikih ataupun aliran-aliran ilmu kalam), yang kemudian men-tarjih-nya (mengunggulkan salah satu pendapat), menjelaskan tata bahasa, serta menggali hukum dari ayat-ayat Al Qur’an. Selain riwayat dari Nabi Saw, sahabat, tabiin, mereka juga mengutip tafsir dari kitab-kitab generasi sebelumnya beserta sanad yang sampai kepada sang pengarang tafsir. Selain itu, maraknya riwayat isra’iliyyat juga mewarnai tafsir generasi ini.
Kebijakan Dinasti Abbasiyyah sangat mendukung terjadinya pelebaran wilayah kajian tafsir pada periode ini. Pada masa Dinasti ‘Abbasiyyah, perkembangan keilmuan Islam sangat pesat, sehingga usaha-usaha penulisan dalam berbagai bidang keilmuan seperti imu gramatika Arab, hadits, sejarah, ilmu kalam, dan lainnya mendapat perhatian yang cukup besar. Mulai periode ini dan periode setelahnya, tafsir yang dulu hanya bersandar pada riwayat hadits Nabi Saw, sahabat dan tabiin (naql, riwayat), mulai bergerak menjalar ke wilayah nalar ijtihad (‘aqli). Penafsiran tidak lagi sekedar hanya menukil riwayat-riwayat dari pendahulunya. Ayat-ayat yang tidak atau belum sempat ditafsiri oleh Nabi Saw maupun sahabat menjadi sasaran empuk untuk dijadikan sebagai ladang penafsiran dengan al ra’yi al ijtihadi. Belum lagi penafsiran-penafsiran pada hal-hal yang tidak begitu penting kaitannya dengan ayat Al Qur’an. Tafsir juga dijadikan sarana pencarian pembenaran bagi sebagian golongan. Apalagi dengan maraknya fanatisme bermazhab dalam bidang fiqih, aliran-aliran ilmu kalam, sampai dengan bidang gramatika Bahasa Arab (nahw sharf). Penafsiran yang dilakukan sesuai dengan golongan atau bidang yang mereka geluti.
Corak tafsir periode pertengahan ini, dengan latar belakang seperti tersebut diatas, maka dapat ditebak kalau tafsir yang muncul ke permukaan pada periode ini akan didominasi oleh kepentingan spesialisasi yang menjadi basis intelektual mufassirnya. Adanya orang-orang tertentu diantara para peminat studi masing-masing disiplin ilmu yang mencoba menggunakan basis pengetahuannya sebagai kerangka pemahaman Al Qur’an, atau bahkan diantaranya yang sengaja mencari dasar yang melegitimasi teori-teorinya dari Al Qur’an, maka muncullah apa yang disebut dengantafsir fighiy, tafsir I’tiqadiy, tafsir sufiy, tafsir ilmiy, tafsir tarbawiy, tafsir akhlaqiy, dan tafsir falsafiy.[11]
Pada era ini, disebut juga dengan era afirmatif dengan nalar ideolois. Pada era ini, muncul fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri yang kemudian mengarah pada sikap taklid buta sehingga mereka nyaris tidak memiliki sikap toleransi terhadap yang lain dan kurang kritis terhadap kelompoknya sendiri. Akibatnya, bagi generasi ini, pendapat tokoh dan imam besar mereka sering kali menjadi pijakan dalam menafsirkan teks Al-Qur’an yang seolah-olah tidak pernah salah, bahkan diposisikan setara dengan posisi teks itu sendiri.[12]
Di sisi lain, sikap fanatisme madzhab dan sektarianisme ini pada akhirnya melahirkan kelompok moderat yang berusaha mencari “sintesa kreatif” atau jalan tengah. Dan dari situ jugalah yang mendorong lahirnya kritik dari para pemikir dan mufassir modern. Mereka burapaya mendekonstruksi dan merekonstruksi model penafsiran yang dinilai telah terlalu jauh menyimpang dari tujuan Al-Qur’an.[13]
Penafsiran – penafsiran seperti ini terus berkembang dan berlanjut hingga melahirkan beratus-ratus kitab tafsir dengan berbagai macam ragam. Meskipun demikian, masih ada kitab tafsir yang tetap berpegang teguh dengan konsep riwayat (ma’tsur) di luar Tafsir al Thabari, seperti Bahr al-Ulum miliknya al Samarqandi (w. 373 H), Mu’alim al Tanzil tafsir karangan al Baghawi (w. 510 H), al Muharrar al Wajiz fi Tafsir al Kitab al Aziz Tafsir karangan Ibn ‘Athiyyah (w. 546 H), kitab Tafsir al Qur’an al Azhim karangan Ibn Katsir (w. 774 H), al- Durr al Mantsur fi al Tafsir al Ma’tsur karya al Suyuthi (w. 911 H).[14]
B. Tafsir Al – Qur’an Pada Periode Modern
Perkembangan selanjutnya dari babakan sejarah penafsiran Al-Qur’an adalah era reformatif yang berbasis pada nalar kritis dan bertujuan transformative. Era ini dimulai dengan munculnya tokoh-tokoh Islam, seperti Sayyid Akhmad Khan dengan karyanya Tafhim Al-Qur’an dan Muhammad Abduh dengan karya tafsirnya Al-Manar yang terpanggil melakukan kritik terhadap produk-produk penafsiran para ulama terdahulu yang dianggap tidak lagi relevan.
Dalam kajian tafsir, sebagaimana penafsiran sebelumnya, tafsir abad modern selalu terdorong untuk menyesuaikan al Qur’an dengan kondisi para mufassirnya. Pengaruh ilmu pengetahuan barangkali merupakan faktor utama dalam melahirkan dan memicu para penafsir memberikan respon. Mereka pada umumnya yakin bahwa umat Islam belum memahami hakikat pesan al Qur’an secara utuh, karena itu mereka belum bisa menangkap spirit rasional Al Qur’an. Kaum modernis mempunyai pandangan misalnya, menafsirkan al Qur’an sesuai dengan penalaran rasional, dengan konsep penafsiran al Qur’an dengan al Qur’an, atau kembali kepada al Qur’an. Mereka juga menentang legenda, fantasi, magic, tahayul dengan cara mengembangkan penafsiran simbolis.
Sebagaimana golongan fuqaha, kaum modernis juga memahami dan menafsirkan Al Qur’an sesuai dengan pemikirannya. Mereka menyakini bahwa penafsiran al Qur’an tidak hanya hak para ulama terdahulu, melainkan terbuka bagi setiap muslim. Dalam pandangan para pembaharu, mufassir klasik selalu menyesuaikan karya mereka dengan keadaan zamannya. Oleh karena itu pada periode sekarang penafsiran diorientasikan ke masa kini.
Semboyan yang selalu diungkapkan adalah bahwa Al Qur’an itu salih li kulli zaman wa makan, dalam pengertian mereka tidak sekedar menerima begitu saja apa yag terungkap secara literal (sebagaimana kebanyakan mufassir terdahulu), namun berusaha memahami dengan selalu mencoba melihat konteks dan makna di balik ayat-ayat Al Qur’an. Dengan kata lain, yang ingin dicari adalah “ruh” atau pesan moral Al Qur’an sendiri. Beberapa tafsir abad modern, antara lain adalah Tafsir Fath al Qadir karya al Shaukani, dan Tafsir Ruh al Ma’ani karya al Alusi.[15]
C. Tafsir Al – Qur’an Pada Periode Kontemporer
Pengertian kontemporer biasanya dikaitkan dengan zaman yang berlangsung. Istilah kontemporer ini sering kali dipakai untuk menunjukkan periode yang tengah kita jalani sekarang, bukan periode yang telah berlalu. Dalam konteks perkembangan tafsir, istilah masa kontemporer terkait dengan situasi dan kondisi tafsir pada saat ini. Dengan demikian, ia dibedakan dengan masa modern. Pada era ini disebut juga dengan era reformatif.
Meski demikian, perkembangan tafsir masa kontemporer sangat tidak bisa dilepaskan dengan perkembangannya di masa modern. Setidaknya, gagasan-gagasan yang berkembang pada masa kontemporer ini sudah bermula sejak zaman modern, yakni pada masa Sayyid Akhmad Khan, Muhammad ‘Abduh dan Rashid Rida. Langkah mereka ini kemudian dilanjutkan oleh para mufassir kontemporer, seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Muhammed Arkoun, dan Hassan Hanafi. Para tokoh ini pada umumnya bersifat kritis terhadap produk penafsiran masa dahulu yang selama ini banyak dikonsumsi oleh umat Islam. Mereka juga cenderung melepaskan diri dari pola berpikir madzhabi. Meskipun pada kedua masa ini (modern dan kontemporer) memiliki persamaan, dan kontemporerpun berangkat dari modern, akan tetapi secara substansial, terdapat banyak perbedaan antara masa modern dengan perkembangan tafsir yang terjadi saat ini (kontemporer).[16]
Berangkat dengan tujuan untuk mengembalikan al Qur’an sebagai hudan li an Nas, metode yang digunakan oleh para mufassir kontemporerpun sedikit banyak berlainan dengan yang digunakan oleh para mufassir tradisional. Kalau para mufassir tradisional kebanyakan cenderung melakukan penafsiran dengan memakai metode tahlily (analitis), maka dalam masa kontemporer penafsiran dilakukan dengan menggunakan metode ijmaly (global), mawdu’iy (tematik) atau penafsiran ayat-ayat tertentu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan modern seperti semantik, analisis gender, semiotik, hermeneutika, dan sebagainya.[17]
Diantara berbagai metode yang berkembang di masa kontemporer, metode mawdu’iy tampaknya merupakan yang paling banyak diminati oleh para mufassir kontemporer. Diantara kitab-kitab tafsir yang menggunakan pendekatan ini adalah al insan fi al Qur’an dan al Mar’ah fi al Qur’an karya Mahmud Abbas al Aqqad, al Riba fi al Qur’an karya Abu al A’la al Mawdudiy, al Aqidah fi al Qur’an karya Muhammad Abu Zahra, dll. Di Indonesia kita juga bisa membaca buku Wawasan al Qur’an karya Quraish Shihab atau Ensiklopedia al Qur’an karya Dawam Raharjo yang juga menggunakan metode tematik ini.[18]
Paradigma tafsir kontemporer dapat diartikan sebagai model atau cara pandang, totalitas premis-premis dan metodologis yang dipergunakan dalam penafsiran Al-Qur’an di era kekinian. Meskipun masing-masing paradigma tafsir memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri, namun ada beberapa karakteristik yang menonjol dalam paradigma tafsir kontemporer, antara lain:
1) Memosisikan Al-Qur’an sebagai Kitab Petunjuk
2) Bernuansa hermeneutis
3) Kontekstual dan berorientasi pada spirit Al-Qur’an
4) Ilmiah, kritis, dan non-sektarian[19]
D. Struktur Dasar Epistemologi Tafsir[20]
1. Era Formatif
| Sumber penafsiran | Metode penafsiran | Validitas penafsiran | Karakteristk dan tujuan penafsiran |
| · Al-Qur’an · Al-Hadits (aqwal ijtihad Nabi) · Qira’at, aqwal dan ijtihad sahabat, tabi’in, atbaut-tabi’in · Cerita israiliyyat · Sya’ir-sya’ir jahiliyyah | · Bil riwayah, deduktif · Disajikan secara oral melalui sistem periwayatan dan disertai sedikit analisis, sebatas kaidah-kaidah kebahasaan. | · Shahih tidaknya sanad dan matan sebuah riwayat · Kesesuaian antara hasil penafsiran dengan kaidah-kaidah kebahasaan dan riwayat hadits yang sahih. | · Minimnya budaya kritisisme, ijmali, praktis, implementatif · Tujuan penafsiran relatif sekedar memahami makna dan belum sampai ke dataran maghza · Posisi teks sebagai subyek dan mufassir sebagai obyek |
2. Era Afirmatif
| Sumber penafsiran | Metode penafsiran | Validitas penafsiran | Karakteristk dan tujuan penafsiran |
| · Al-Qur’an · Al-Hadits (aqwal ijtihad Nabi) · Akal (ijtihad), dan akal ini lebih dominan daripada Al-Qur’an dan Hadits · Teori-teori keilmuan ditekuni mufassir | · Bil ra’yi, deduktif, tahlili · Menggunakan analisis kebahasaan dan cenderung mencocok-cocockan dengan teori-teori dari disiplin keilmuan atau madzhab sang mufassir | · Kesesuaian antara hasil penafsiran dengan kepentingan penguasa, madzhab (aliran), dan ilmu yang ditekuni oleh para mufassir | · Ideologis, sekterian, atomistic, repetitive · Ada pemaksaan gagasan non-qur’ani · Cenderung truth claim dan subyektif · Penafsiran bertujuan untuk kepentingan kelompok, mendukung kekuasaan, madzhab, atau ilmu yang ditekuni mufassir · Posisi mufassir sebagai subyek sementara teks sebagai obyek |
3. Era Reformatif
| Sumber penafsiran | Metode penafsiran | Validitas penafsiran | Karakteristk dan tujuan penafsiran |
| · Al-Qur’an · Realitas-akal yang berdialektika secara sirkular dan fungsional · Sumber hadits jarang digunakan · Posisi teks Al-Qur’an dan mufassir sebagai obyek dan subyek sekaligus | · Bersifat interdisipliner, mulai dari tematik, hermeneutic, hingga linguistic, dengan pendekatan sosiologis, antropologis, historis, sains, semantic, dan disiplin keilmuan masing-masing mufassir | · Ada kesesuaian antara hasil penafsiran dengan proposisi-proposisi yang dibangun sebelumnya · Ada keseuaian antara hasil penafsiran dengan fakta empiris · Hasil penafsiran bersifat solutif dan sesuai kepentingan transformasi umat | · Kritis, transformative, solutif, non-ideologis · Menangkap “ruh” Al-Qur’an · Tujuan penafsiran adalah untuk transformasi sosial, serta mengungkap makna dan sekaligus juga maghza (significance) |
[1] Abdul Mustaqim, dalam bukunya Epistemologi Tafsir Kontemporer membagi era perkembangan tafsir menjadi tiga, antara lain adalah, pertama: era formatif-klasik, yang di dalam penafsiran terhadap al-Qur’an lebih berpegang pada teks, lebih lanjut disebut tafsir bil ma’tsur, yang lebih menggunakan metode deduktif. Era ini terjadi pada abad awal, yakni Nabi, sahabat, dan tabi’in. kedua: era afirmatif dengan nalar ideologis. Yakni suatu penafsiran yang dipengaruhi oleh fanatic madzhab, yang mengakibatkan al-qur’an ditafsirkan sesuai dengan ideology yang dianut oleh suatu madzhab, akibatnya terjadi pemerkosaan pemaknaan teks. Era ini terjadi pada abad kedua. Ketiga: era reformatif dengan nalar kritis. Era ini terjadi pada era modern-kontemporer yang dilakukan oleh Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla yang kemudian diteruskan oleh ulama-ulama kontemporer seperti fazlur rahman, Muhammad syahrur, dan lain-lain. Ciri dari penafsiran ini adalah menghindari berpikir madzhabi, dan menfsirkan dengan nalar yang kritis.
Lihat, Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. 44-52.
[2] Abdul Mustaqim, Op.Cit, hlm. 44-45.
[3] Seyyed Hossein Nashr, Islamic Life and Thought, (Albany: State University Of New York Press, 1981), hlm. 59.
[4] M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masayarakat Umat, cet. XVIII, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 73.
[5] Az-Zarkasyi, AL-Burhan Fi Ulumil Qur’an, jld. II, (Mesir: Isa Al-Bab AL-Halabi, 1972), hlm. 159.
[6] Lihat, Muhammad Yusuf, dkk, Ulumut Tafsir 3, (Jakarta: DEPAG, 1997), hlm. 53.
[7] Manna’ Khalil Al-Qaththan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, cet. 11 (Jakarta: Halim Jaya, 2007), hlm. 476.
[8] ibid
[9]http://pwknw.blogspot.com/2009/11/sejarah-pertumbuhan-dan-perkembangan.html, diakses 11 Desember 2011
[10] Tim Forum Karya Ilmiah RADEN, Al Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah, dan Tafsir Kalamullah,….h.211-213.
[11] M. Zaenal Arifin, Pemetaan Kajian Tafsir (Perspektif Historis, Metodologis, Corak, dan Geografis),….h.18.
[12] Abdul Mustaqim, Op.Cit, hlm. 49.
[13] Abdul Mustaqim, Op.Cit, hlm. 49-50.
[14] http://asmaulchusna-nana.blogspot.com/2012/01/pertumbuhan-dan-perkembangan-tafsir.html. diakses pada tgl. 12 mei 2012, pkl. 13.30.
[15]M. Zaenal Arifin, Op.Cit, hlm. 22.
[16] Abdul Mustaqim, Op.Cit, hlm. 52.
[17]M. Zaenal Arifin, Op.Cit, hlm .24.
[18]M. Zaenal Arifin, Op.Cit, hlm. 26.
[19] Lihat, Abdul Mustaqim, Op.Cit, hlm. 53-65.
[20]Abdul Mustaqim, Op.Cit, hlm. 45,51,84.